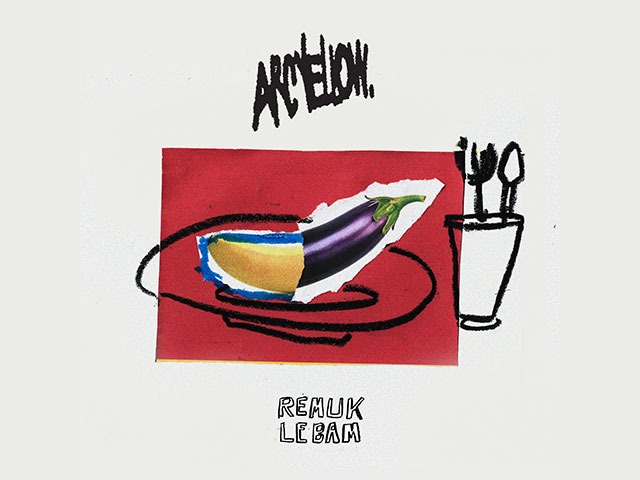Perayaan Musik Padepopan yang telah digelar di Terminal Jatijajar pada 7 desember 2025 silam, menyelipkan sebuah diskusi Saling Sapa, yang kali ini “dibajak” oleh Kolase Kultur. Saling Sapa merupakan program bulanan Pemuda Dalam Gang sebagai ruang bertukar gagasan dengan tujuan mendukung kerja-kerja komunitas khususnya dalam skena musik Depok. Setelah “diakuisisi”, Kolase Kultur menjadikan Saling Sapa …
Rangkuman Diskusi Saling Sapa di Festival Musik Padepopan 2025

Perayaan Musik Padepopan yang telah digelar di Terminal Jatijajar pada 7 desember 2025 silam, menyelipkan sebuah diskusi Saling Sapa, yang kali ini “dibajak” oleh Kolase Kultur. Saling Sapa merupakan program bulanan Pemuda Dalam Gang sebagai ruang bertukar gagasan dengan tujuan mendukung kerja-kerja komunitas khususnya dalam skena musik Depok. Setelah “diakuisisi”, Kolase Kultur menjadikan Saling Sapa berupa ruang temu lintas praktik, antara musik, seni, dan gerakan sosial.
Diskusi singkat berdurasi 15 menit itu dipandu oleh Setyo Manggala, seorang aktivis dan periset yang aktif di komunitas Lensa Anak Terminal Depok. Menghadirkan tiga narasumber; Reino sebagai pengamat budaya populer yang aktif di pergerakan Indie Pop Depok, Angelissa Marissa sebagai seniman sekaligus pekerja seni media, dan Fajrin Dedi a.k.a Aceh sebagai aktivis dari Gerakan Aceh Mencukur. Mereka berbicara dari pengalaman masing-masing tentang keterbatasan ruang, praktik kesenian dalam kota, dan peran seni dalam aktivisme.
Diskusi dibuka dengan refleksi situasi sosial terkini, yaitu duka atas bencana kemanusiaan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ditegaskan pula oleh Setyo sebagai bencana ekologis; akibat ulah manusia, lebih tepatnya ulah oligarki dan turunannya, bukan semata-mata alam. Lalu, percakapan bergerak ke konteks lokal Depok, kota dengan potensi kreatif yang cukup besar, namun minim ruang yang benar-benar berpihak pada warganya sendiri.
Reino: Musik, DIY, dan Paradoks Ruang
Reino menyoroti kondisi ekosistem musik di Depok yang penuh paradoks. Di satu sisi, kota ini memiliki venue baru (seperti Depok Open Space); di sisi lain, ruang tersebut jarang benar-benar dapat diakses oleh komunitas. Dalam kondisi itu, semangat DIY (Do It Yourself) yang digalakkan oleh Reino dan kawan-kawan Indie Pop menjadi kunci keberlanjutan dalam aktivitas berkaryanya.

Alih-alih menunggu dukungan struktural, Reino dan jejaringnya memilih membangun blokade (ruang sendiri) melalui produksi karya. Konsistensinya membawa Depok menjadi tuan rumah untuk musisi indie pop dari luar negeri. Di tengah banjirnya informasi dan algoritma media sosial yang tidak bisa kita pilih, militansi dianggap sebagai cara untuk membangun kesadaran atau exposure secara organik.
Dalam pelaksanaannya, sikap ini juga tercermin pada pilihan etis. Reino menegaskan sikapnya menolak sponsor yang destruktif seperti rokok dalam konser musik. Secara personal, bukan sebagai larangan moral, melainkan bentuk tanggung jawabnya. Ia tidak ingin menjadi rujukan bagi praktik yang tidak ingin ia wariskan kepada audiensnya.
Angel: Seni, Kehilangan Ruang, dan Eksodus Seniman
Dari sudut pandang seni rupa dan praktik seni digital, Angel menyoroti persoalan yang tak kalah mendasar dari hilangnya ruang kesenian di Depok. Pembongkaran gedung kesenian dan minimnya ruang presentasi karya yang berpihak, menurutnya mengakibatkan seniman lokal memilih berpameran ke luar kota atau bahkan ke luar negeri. Sementara ruang di dalam kota sering diisi oleh seniman dari luar.

Bagi Angel, ruang tidak harus dimaknai sebagai bangunan fisik semata, lebih tepatnya sebagai social space untuk tumbuh. Ketika ruang itu tidak tersedia, ekosistem seni yang digadang-gadangkan dengan demikian hanya berupa omongan belaka.
Ia juga mengungkapkan bahwa Depok sebenarnya punya bekal utama. Seperti seniman muda yang terus melahirkan karya dengan praktik kontemporernya. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa memprioritaskan pelaku di dalam kota, termasuk membentuk basis audiens dan konsumen seni itu sendiri.
Aceh: Musik sebagai Ujung Tombak Aktivisme
Aceh dari Gerakan Aceh Mencukur menerangkan posisi musik sebagai medium efektif dalam kerja-kerja aktivisme. Menurutnya, musik beroperasi pada wilayah yang paling dasar; pendengaran dan ingatan. Orasi mudah dilupakan, lagu yang sekarang aksesnya begitu luas, dapat membentuk kesadaran kolektif secara perlahan.
Dalam konteks isu lingkungan, Aceh menilai ketidakpedulian masyarakat Depok sering muncul karena absennya pengalaman langsung. Selama bencana dirasa “jauh”, kepedulian warga pun minim. Aceh menyatakan bahwa musik dengan lirik dan figur-figur yang diidolakan, berpotensi menjembatani jarak itu dan menghidupkan kembali kesadaran akan relasi manusia dengan alam. Aceh menyebutnya sebagai “ibu” nan kian diabaikan.

Tema lagu tidak harus selalu politis secara eksplisit. Lagu cinta pun, pada dasarnya, adalah soal relasi dan kepedulian, bisa menjadi nilai yang sama dan seharusnya diterapkan pada kehidupan kita. Sependek pengetahuannya, hanya Olsam satu-satunya band asal Depok yang berhasil menyerukan kepedulian terhadap lingkungan lewat lagunya Jaga & Rawat Ciliwung Kita.
Setyo: Pentingnya Solidaritas dan Bergerak Bersama
Setyo sebagai moderator juga memantik arah berlangsungnya diskusi singkat ini. Ia secara tidak langsung memberikan tanggapan bahwa ketidakberpihakan infrastruktur dalam kota tidak boleh menjadi alasan kita berhenti bergerak. Baik itu melalui musik, seni, maupun gerakan. Para narasumber akhirnya sepakat mengenai kerja-kerja kecil yang konsisten dan berbasis solidaritas dapat menjadi fondasi utama untuk membangun sebuah ekosistem berkelanjutan. Depok mungkin belum ideal, tetapi telah dilimpahkan dengan sumber daya yang mumpuni. Tinggal bagaimana semua itu terus diperjuangkan melalui kerja-kerja kolektif dan “perawatan”.