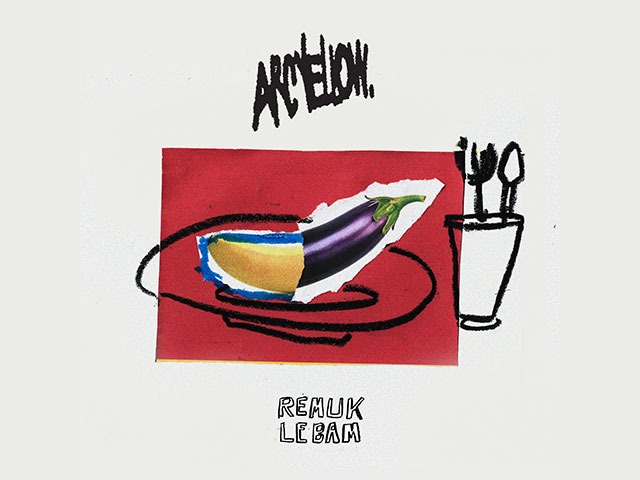Film animasi Indonesia Merah Putih: One For All yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 14 Agustus 2025 tuk menyambut Hari Kemerdekaan, menuai kritik tajam dari publik. Diproduksi oleh Perfiki Kreasindo dengan anggaran yang dikabarkan mencapai Rp6,7 miliar, karya ini diharapkan menjadi kebanggaan animasi nasional. Namun, dari trailer yang beredar, banyak warganet menilai kualitasnya terlalu lawas, …
3 Sudut Pandang 3D Artist Asal Depok Tentang Film Animasi Merah Putih One For All

Film animasi Indonesia Merah Putih: One For All yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 14 Agustus 2025 tuk menyambut Hari Kemerdekaan, menuai kritik tajam dari publik. Diproduksi oleh Perfiki Kreasindo dengan anggaran yang dikabarkan mencapai Rp6,7 miliar, karya ini diharapkan menjadi kebanggaan animasi nasional. Namun, dari trailer yang beredar, banyak warganet menilai kualitasnya terlalu lawas, dengan karakter yang kaku dan visual di bawah standar.
Film animasi ini menceritakan tentang delapan anak dari berbagai daerah Indonesia dari Betawi hingga Papua yang bersatu untuk menyelamatkan bendera merah putih. Bendera itu hilang tiga hari sebelum upacara kemerdekaan. Dari situlah cerita Merah Putih “dimulai”.
Fakta bahwa proses produksinya baru dikerjakan pada Juni 2025, hanya dua bulan sebelum perilisan, membuat publik bertanya-tanya soal kesiapan tim produksi di baliknya.
“Ngapain ngabisin anggaran kalau emang nggak niat bikin,” kata warganet.
Toti Soegriwo, kreator sekaligus produser film ini, telah bersuara. Melalui akun Instagram pribadinya, ia memilih menanggapi kritik dengan santai. “Senyumin aja, komentator lebih pandai dari pemain. Banyak yang mengambil manfaat juga kan? Postingan kalian viral kan?” tulisnya.

3 Sudut Pandang 3D Artist Asal Depok
Kami mencoba melihat fenomena ini dari sudut pandang para praktisi 3D artist asal Depok, di mana mereka telah berpengalaman dalam industri dan memahami betul proses kreatif, terutama teknis produksi animasi. Kami ingin mengetahui respons sekaligus bertanya: apakah hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan teknis, pilihan gaya visual, atau faktor lain dalam proses produksi?

Z. A Setiawan (biasa dipanggil Z), seniman yang memiliki hobi 3D art melihat film ini sebagai sebuah ekspresi seni, meskipun secara teknis terlihat terburu-buru.
“Menurut gue yang bukan 3D artis amat, film ini seni. Di baliknya mungkin ada teknis dan arahan yang belum matang, atau kita nggak tahu gimana kondisi di belakangnya. Tapi ini gebrakan, dan ini seni indie.” ucapnya sambil tertawa.
“Tapi kalau abis sampai 6,7 M, kaco, sih!” ujar Z heran. Z yang juga aktif di ekosistem musik Depok merasa harus ada transparansi soal bagaimana film ini bisa masuk ke dalam ruang pemutaran bioskop komersil.
Fakhri Alwani seorang 3D artist dan Motion Designer yang sudah menggeluti bidang tersebut selama 4 tahun lamanya menilai masalah utama bukan pada keterbatasan teknis atau gaya visual.
“Ini ada faktor lain yang ngebuat filmnya jadi kurang banget, karena kalau kita bahas soal teknis dan gaya visual di indonesia itu udah banyak studio 3D yang bagus dan proper untuk mengerjakan sebuah animasi yang lebih dari film ini,” ucapnya.
Ia tidak menjelaskan secara gamblang apa penyebabnya, tapi yang jelas film ini tidak bisa dipertanggung jawabkan.
“Faktor utamanya itu ada ‘udang di balik batu’. Masnya pasti paham maksud saya,” tutupnya sambil tertawa.

Samuel Christian sebagai senior 3D artist dengan pengalaman lebih dari enam tahun di industri game dan animasi internasional, memberikan analisis mendalam soal isu ini.
Ia menyatakan kritik warganet sangat bisa dimengerti mengingat anggaran yang dikabarkan mencapai Rp 6,7 miliar. Ia menegaskan bahwa kemampuan SDM Indonesia, bahkan dengan perangkat open source seperti Blender, sangat mumpuni dan dapat menghasilkan karya setara Netflix atau Pixar.
“Untuk sebuah proyek dengan anggaran yang dikabarkan mencapai Rp6,7 miliar, wajar jika ekspektasi publik tinggi,” ujarnya.
Ia juga menyebut beberapa masalah teknis yang mendasar. Seperti asset yang dikabarkan dibeli dari sebuah marketplace dengan harga murah.
“Dari sumber yang beredar asset bukan dibuat sendiri, tapi dibeli. Menariknya, kualitas presentasi asset aslinya justru terlihat lebih baik dibanding hasil render akhir di film ini. Setelah diintegrasikan ke dalam animasi, kualitasnya malah turun, entah karena proses penyatuan yang kurang baik atau pipeline produksi yang tidak optimal.” ucapnya.
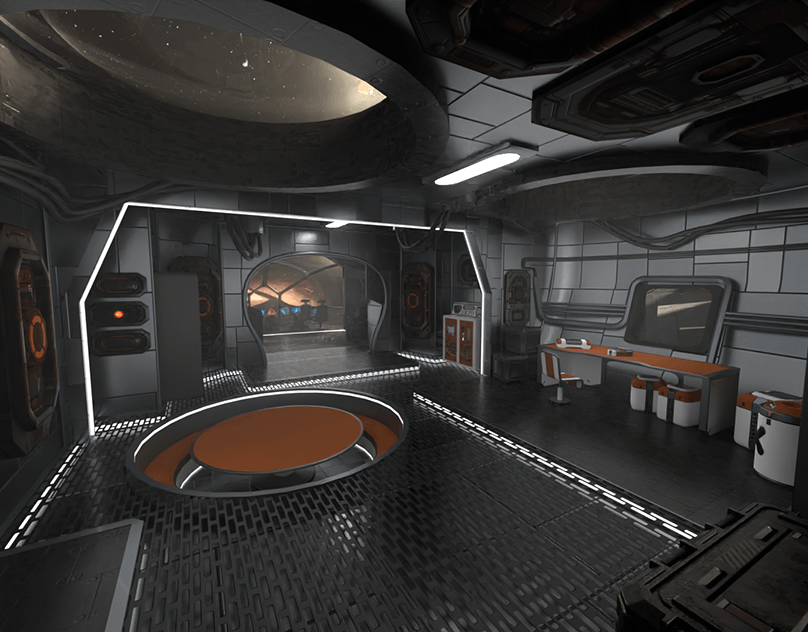
Inkonsistensi gaya visual: karakter, lingkungan, dan properti terkesan tidak menyatu sebagai satu dunia artistik yang menandakan art direction dan perencanaan visual yang kurang matang.
“Seolah-olah setiap elemen berasal dari proyek berbeda. Hal ini menandakan kurangnya perencanaan visual dan art direction yang matang, sehingga hasil akhirnya terlihat tergesa-gesa dan asal-asalan,” katanya.
Samuel berpendapat, seharusnya dengan durasi lebih pendek dan plot lebih ramping, kualitas visual bisa jauh lebih baik dengan anggaran tersebut. Ia mencontohkan film Jumbo sebagai bukti bahwa dengan perencanaan dan SDM yang dimiliki, Indonesia mampu menghadirkan animasi berkualitas tinggi.
“Saya paham bahwa membuat animasi memang mahal dan tidak mudah, tapi saya tidak setuju jika dibilang sumber daya manusia di Indonesia hanya mampu menghasilkan kualitas seperti ini,” ujarnya.
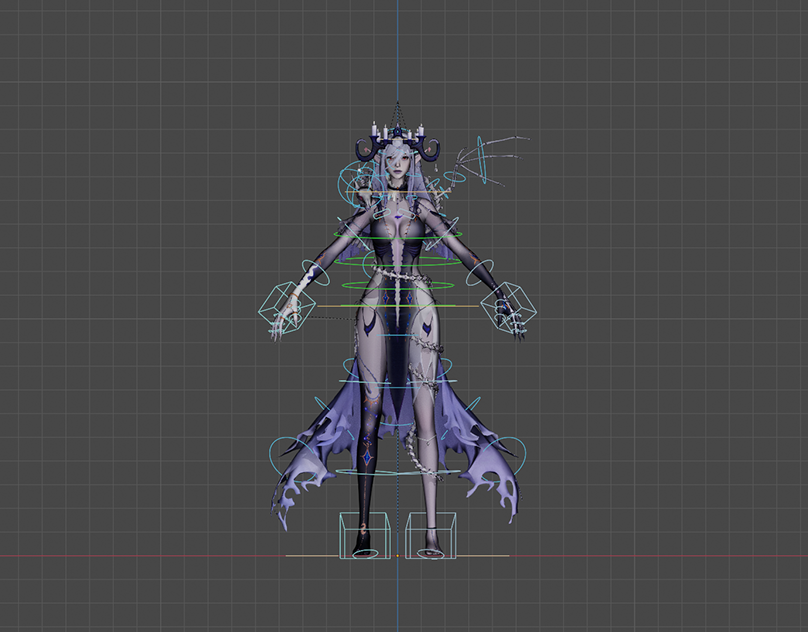
Potret Industri dan Melihat Kondisi Terkini Industri Animasi Indonesia
Jauh sebelum film Merah Putih: One For All diproduksi, industri animasi Indonesia tengah menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI) tahun 2020, subsektor film, animasi, dan video tumbuh 153% dalam kurun 2015-2019, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 26%. Pendapatan melonjak dari sekitar Rp 238 miliar pada 2015 menjadi lebih dari 602 M pada 2019, meski sempat turun ke 510 M di masa pandemi.
Bersumber dari Reuters, kesuksesan film Jumbo menjadi bukti nyata potensi industri, menyandang status film animasi terlaris di Indonesia dan Asia Tenggara, melampaui Frozen 2 dengan pendapatan lebih dari US$ 20 juta dan lebih dari 9,6 juta penonton.
Meskipun film Merah Putih: One For All dilatarbelakangi semangat patriotik menyambut kemerdekaan, kritik publik ini mencerminkan masih perlunya evaluasi menyeluruh, termasuk proses kurasi bioskop di Indonesia untuk menghadirkan film-film yang berkualitas.
Indonesia memiliki banyak talenta 3D artist yang berpengalaman di kancah internasional. Kasus Merah Putih: One For All seakan menjadi pengingat bahwa teknologi dan SDM mumpuni di Indonesia sangat melimpah. Bagi penonton, kontroversi ini mungkin memicu rasa penasaran untuk tetap menonton. Bagi pelaku industri, ini adalah studi kasus berharga bahwa sebuah karya bukan cuma berbicara soal ide, tetapi yang lebih penting adalah soal eksekusi yang terukur.