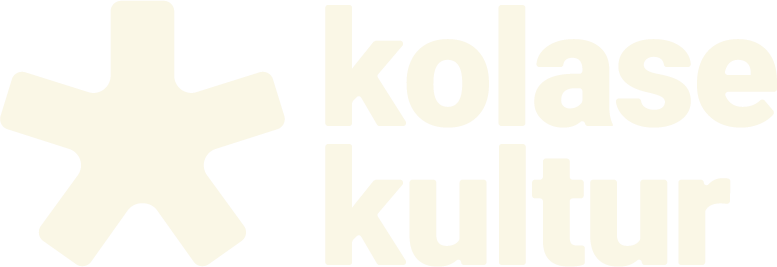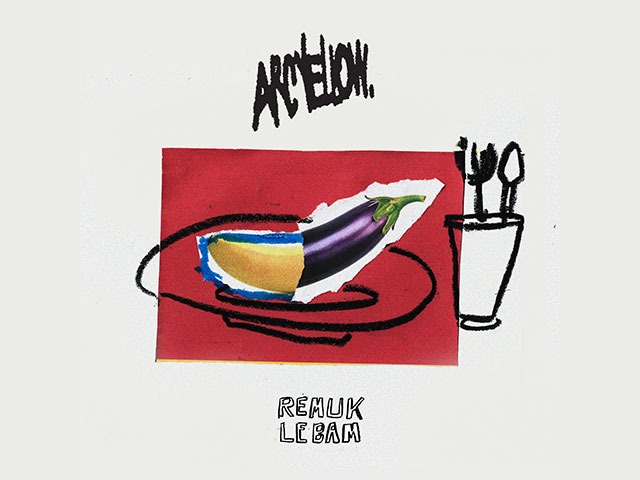Belum genap 6 tahun saya mencicipi perairan di dunia musik, setelah sebelumnya asyik berenang-renang di bidang seni lainnya; teater dan film. Musik–yang meski sudah saya cintai sejak kecil, akhirnya baru saya geluti–memberi saya sepasang mata yang segar. Ia menjadi media yang memaksa saya mengenali sisi diri yang belum pernah terlatih, khususnya soal cara mempresentasikan diri …
Perempuan: Etalase dan Kotak Kaca

Belum genap 6 tahun saya mencicipi perairan di dunia musik, setelah sebelumnya asyik berenang-renang di bidang seni lainnya; teater dan film. Musik–yang meski sudah saya cintai sejak kecil, akhirnya baru saya geluti–memberi saya sepasang mata yang segar. Ia menjadi media yang memaksa saya mengenali sisi diri yang belum pernah terlatih, khususnya soal cara mempresentasikan diri sebagai perwujudan langsung dari karya kami sendiri. Setelah sebagian besar waktu saya di panggung dilakukan sebagai aktor–yang masih belajar menjadi merdeka–tampil di panggung musik menyadarkan saya bahwa kini tidak ada lagi topeng jujur yang boleh saya pakai selain milik saya sendiri. Tidak ada lagi karakter fiktif yang menjadi sekstan bagi tiap gerik, justifikasi bagi segala jenis emosi. Kini, yang masih tinggal hanyalah naskah yang dimusikkan; juga kami, si pencerita. Maka saya mendapati diri saya dalam keadaan yang paling rapuh, paling telanjang–menyanyikan isi diari kami sendiri.
Namun, di tengah kegamangan menyibak lapis demi lapis kebaruan di tanah segar ini, ternyata saya masih dihadapkan pada suatu persoalan usang. Problematika yang tak pernah hilang dalam bidang apapun, termasuk kesenian; seksisme.
Seperti halnya berbagai bidang lainnya, musisi perempuan masih terhitung sebagai minoritas dalam dunia musik. Meski belum ada data pasti tentang persentase musisi perempuan dan laki-laki di Indonesia, namun dalam konteks global, musisi laki-laki masih mendominasi. Musisi perempuan jarang mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Tak jarang, nama penulis lagu perempuan juga tak dicantumkan dalam kredit. Dalam beberapa tahun terakhir, tangga di industri musik global didominasi oleh laki-laki. Penelitian dari Dr. Stacy L. Smith, Dr. Katherine Pieper, Karla Hernandez, dan Sam Wheeler dari USC Annenberg yang diterbitkan pada tahun 2021 pun menyimpulkan bahwa persentase perempuan pada tangga lagu global hanya berada di angka 21,6% selama jangka waktu 9 tahun; sejak tahun 2012. Dalam berbagai bentuk tangga lagu baik solo, duo, ataupun band, perempuan memiliki persentase yang sangat sedikit dengan rata-rata tidak mencapai 10% di setiap kategorinya (Audionetwork, 2022). Begitu juga dalam acara penghargaan musik besar di dunia, yakni Grammy Awards, persentase musisi perempuan masih sangat jauh ketimbang laki-laki. Dalam evaluasi selama 11 tahun terakhir, nominasi dalam kategori utama didominasi oleh laki-laki dengan angka 86% sedangkan nominasi perempuan hanya mencapai angka 13,9% (Billboard, 2023) (Pinasti & Trisnaningtyas, 2025).
Sejak awal, seorang kawan memang memberi pengantar yang pahit–anekdot getir tentang nasib banyak musisi perempuan dari kota asalnya. Sudah sedikit, musisi perempuan masih harus pula menerima berbagai koersi: minuman keras yang harus ditenggak, kontak fisik yang tidak diinginkan–semua hanya karena mereka memiliki bakat musik yang ingin diamalkan, namun terlahir dengan vagina. Seksisme ini jugalah yang membuat mereka berpikir ulang jutaan kali, hingga akhirnya berpindah haluan dan mundur sebagai musisi. Pilihan yang tentunya tak bisa disalahkan, namun secara tak dapat dihindari, menjadikan dunia permusikan semakin maskulin. Segalanya bagaikan lingkaran setan; semakin seksis, semakin tak nyaman, semakin banyak yang mundur, dan musisi perempuan pun semakin minoritas.
Kemudian, ternyata kisah getir itu berkali-kali tertulis ulang dengan versinya sendiri dalam perjalanan bermusik saya yang masih seumur jagung ini; seorang kenalan di dunia musik memanggil saya dengan sebutan “betina” dalam pertemuan pertama (dan terakhir) kolaborasi kami, sebuah program musik di kota dingin Jawa Barat melontarkan pertanyaan seksis saat sesi wawancara, terlebih lagi ribuan jokes mesum, reduktif, hingga persuasi tak senonoh yang terjadi dalam lingkungan musisi di program religi salah satu stasiun TV nasional. Seluruhnya terjadi dalam kurun waktu kurang dari 6 tahun, (dan mungkin membutuhkan artikelnya sendiri, masing-masing).
Itulah mengapa ketika sebuah pihak penyelenggara acara musik membawa janji “ruang aman bagi seluruh peserta, termasuk perempuan” pada sebuah technical meeting online, separuh dari kekhawatiran kami seolah mendapat obat. Hal ini membuktikan satu hal; bahwa standar perlakuan layak pada perempuan telah menjadi sedemikian rendahnya sehingga janji akan tiadanya perlakuan tak pantas, lantas terasa bagai oasis.
Namun, sayangnya, oasis itu begitu cepat bertransformasi menjadi tanda tanya ketika kami sampai di lokasi. Kerumunan yang didominasi oleh laki-laki; dari line up penampil, pekerja, sampai penonton, menimbulkan keraguan kami yang pertama. Keraguan yang kelewat lancar bertumbuh sebab didasari oleh pengalaman, meski dengan keras kepala, berkali-kali kami tampikkan. Kami ingin percaya pada oasis dan kebenaran di balik jargon.
Nyatanya, sepanjang malam bergulir, “ruang aman” yang dijanjikan ternyata terlalu luput untuk didirikan oleh pihak yang berjanji. Kami masih menyaksikan–dan menerima–sikap senada dengan acara seni lainnya yang bahkan tak pernah menjanjikan “ruang aman itu” sama sekali. Candaan dan senggakkan yang sarat akan tatapan lelaki (male gaze); aksi panggung dengan gestur seksual melalui perspektif maskulin, seolah-olah panggung diubah menjadi warung tongkrongan tempat melempar inside joke kepada kaum lelaki sejawat, dan lupa–atau bahkan tidak mengindahkan sama sekali–bahwa kelompok yang tengah mereka kangkangi dalam candaan itu turut menjadi bagian dari kerumunan.
Sebagai perempuan yang kebetulan menjadi penampil, hal itu juga terasa dari cara kerumunan mayoritas merespon kami. Terlepas dari preferensi musik penonton dan genre yang mungkin tidak selalu cocok, kerumunan malam itu membuat kami merasa tidak memiliki tempat untuk dipandang sebagai manusia utuh; tatapan justru kami terima saat kami diam dan berjalan sendiri, sedangkan, saat kami mencoba membangun relasi, konversasi, diskusi, atau bahkan koneksi dari atas panggung tempat kami tampil, pandangan itu mendadak absen sepenuhnya. Berkali-kali kami menegaskan kehadiran kami melalui konversasi, dan berkali-kali pula kolega laki-laki luput memandang dan mendengar kami. Kami dikucilkan dari sebuah percakapan tentang karya kami sendiri! Tak ada satu pun diskusi karya yang melibatkan kami, tentang baik-buruknya, apresiasi-kritiknya, sebab tampaknya, kerumunan maskulin ini lebih suka mendengar pembahasan karya kami melalui suara lain yang lebih familiar bagi mereka–yakni suara sesama laki-laki.
Sayangnya, lingkaran percakapan yang enggan membuka itu kelewat banyak kami temui di acara seni mana pun. Seolah-olah pekerjaan kami telah rampung setelah tampil dan dipandang-pandangi, entah untuk apa. Tak layak untuk diajak berdiskusi. Maka, keraguan yang bertunas di awal malam tadi kini berbuah menjadi pertanyaan; untuk apa dan untuk siapa kami berada di sini? Tak mungkin ada “ruang aman bagi perempuan” jika “ruang” itu sendiri pun tak ada. Sungguh amat disayangkan jika sebuah acara kesenian, apalagi yang didukung oleh media partner pengusung kesetaraan gender dan penciptaan ruang aman bagi perempuan, justru memposisikan kolega perempuannya di tempat mereka dilihat sebagai daging, atau tidak sama sekali–bukan di mata si pengusung janji, melainkan oleh kolega dan kerumunannya sendiri.
Seorang kawan menyampaikan perspektif lain–yang memang marak ditemukan dalam masyarakat (patriarkal); absensi pandangan tersebut mungkin merupakan bentuk rasa segan, sebab kami adalah perempuan yang sudah memiliki pasangan. Terlebih lagi, mereka turut hadir di saat acara.
Lantas, segan pada siapa?
Dari dekat, mungkin sikap ini nampak bagai respek, namun jika kita mundur dan melihat gambaran secara keseluruhan, sikap ini sesungguhnya sangat reduktif–mengapa status hubungan pribadi kami menjadi faktor penentu akan layak atau tidaknya membangun sebuah diskusi profesional antar sesama pelaku kesenian? Akankah sikap yang sama diberlakukan jika kami adalah laki-laki? Jika sikap menghindari interaksi atas dasar “segan” pada perempuan hanya berlaku dengan adanya “pasangan”, maka kita sebagai masyarakat tak bisa menyangkal bahwa pandangan kepada perempuan hanya dilemparkan ketika kami tengah diperhitungkan sebagai pasangan atau target potensial; dan ketika kami telah tercoret dari daftar kemungkinan–sebagai bentuk “segan” pada sesama lelaki–maka perempuan tak lagi dipandang, sebab, bagi masyarakat patriarkal, esensinya pupus sudah.
Ketika perempuan hanya dipandang tak lebih dari sekadar “posesi” atau “potensi posesi”–tanpa mengindahkan opininya, karyanya, suaranya, bahkan kemanusiaannya, dalam konteks apa pun–maka tak mungkin perempuan dihargai dengan setara, selayaknya manusia, di ruang kesenian atau ruang mana pun.
Keluputan ini, bagi saya, adalah perwujudan dari niat baik yang belum digenapi dengan pengawalan. Dalam acara yang digodok secara kolektif, satu tangan memang memeluk begitu banyak tanggung jawab. Perlu dicatat bahwa memang ada upaya menuju ruang kesenian yang lebih inklusif, namun janji yang tidak dibarengi dengan pengawasan, conditioning, dan penyaringan yang mendetil pada ruang akan menjadi jargon semata. Nyatanya janji serupa tidak menyentuh siapa-siapa, tidak bisa menjamin semua pihak untuk serta merta bekerjasama, dan pastinya, tidak bisa mengubah mindset patriarki dalam semalam.
Lantas, bagaimana caranya membuat ruang kesenian yang aman dan nyaman untuk semua pihak? Sebab, ternyata rasa aman pada perempuan tidak bisa koeksis dengan massa yang tak terkurasi jika kolam besarnya masih sangat terkontaminasi oleh patriarki dan misogini. Jika ruang aman untuk perempuan hanya bisa tercipta melalui dibentuknya kolektif dengan orang-orang pilihan–mungkin melibatkan lebih banyak perempuan sebagai pekerja dan peserta, atau adanya penyaringan sedemikian rupa–artinya masyarakat kita masih jauh dari kata berhasil; inilah masyarakat yang sebegitu tidak mampunya menghormati perempuannya, sehingga, jika tidak mau dipandang sebagai objek atau barang jajakan, perempuan harus lari ke tempat yang lebih tertutup; ruang bentukan kita sendiri tempat karya kita bisa dilihat, transparan, namun terlindung. Dari barang jajakan di etalase, ke ruang aman sebening kaca. Dari etalase ke kotak kaca.
Lalu, seberapa bebaskah kita dalam ruang ekspresi kita sendiri? Entah. Yang saya pahami saat ini hanya satu, bahwa kita masih sangat jauh dari utopia sederhana kita; “ruang aman bagi perempuan dalam dunia kesenian.”