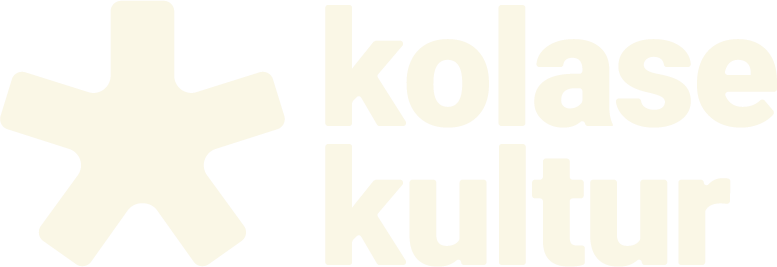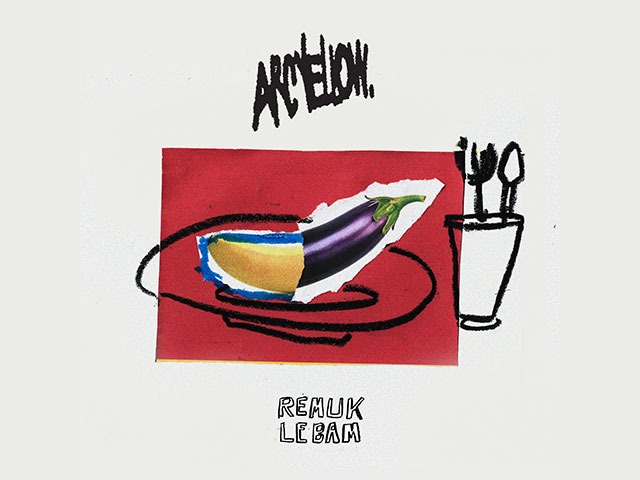Isu kewajiban pembayaran royalti untuk penggunaan musik di ruang publik komersial kembali memicu perdebatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menegaskan bahwa musik yang diputar di ruang publik komersial (resto, kafe, dan hotel) dikategorikan sebagai pertunjukan publik dan wajib membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Kasus ini …
Royalti Musik di Ruang Publik: Suara Para Pemilik Ruang di Depok

Isu kewajiban pembayaran royalti untuk penggunaan musik di ruang publik komersial kembali memicu perdebatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menegaskan bahwa musik yang diputar di ruang publik komersial (resto, kafe, dan hotel) dikategorikan sebagai pertunjukan publik dan wajib membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
Kasus ini kembali mencuat setelah Mie Gacoan dilaporkan LMKN karena tidak membayar royalti atas musik yang digunakan sebagai backsound. Reaksi pun bermunculan: sebagian mendukung demi menghargai karya musisi, sebagian lain mempertanyakan metode penarikan, pembagian, dan relevansi kebijakan tersebut terutama bagi pelaku usaha mikro dan kafe kecil.
Antara Menghargai Karya dan Realitas Usaha
Koko, pemilik Warnoes, mengaku baru tahu bahwa langganan premium layanan musik seperti Spotify atau Apple Music tidak mencakup lisensi komersial.
“Kita kira kalau sudah beli paket premium, itu sudah termasuk lisensi. Selama ini kita memang pakai layanan tersebut,” ujarnya.
Ia mendukung penghargaan terhadap karya musik dan kerap memutarkannya untuk memperkenalkan ke pengunjung. Namun, ia menilai kewajiban royalti lebih layak diterapkan jika ada pemasukan langsung dari penonton, misalnya melalui tiket masuk.
“Kalau komersil dalam arti tiket masuk, oke. Tapi kalau dalam situasi publik yang tidak mewajibkan orang belanja, agak berat,” tambahnya.
Pandangan ini mencerminkan cara sebagian pelaku usaha di Depok melihat royalti sebagai biaya tambahan di luar HPP. Dalam situasi publik yang tidak menghasilkan transaksi per kepala pengunjung, biaya tersebut dianggap sulit ditanggung. Padahal, menurut PP No. 56 Tahun 2021 dan pernyataan DJKI, penggunaan musik di ruang publik komersial tetap tergolong pertunjukan publik dan wajib membayar royalti, terlepas dari ada atau tidaknya tiket atau transaksi langsung.
Sementara itu, Ebo dari Kios Warga menilai kebijakan ini “cukup berat” jika diterapkan apa adanya. Kios yang juga berfungsi sebagai ruang komunitas musik ini sering memutar rilisan fisik, terutama kaset, dan jarang mengandalkan playlist digital.
“Kalau dihitung-hitung, kita lebih sering muter lagu daripada pendapatan yang masuk,” katanya sambil tertawa. Ia mendukung jika royalti benar-benar sampai ke musisi, tetapi mempertanyakan relevansi penarikan yang tidak membedakan antara usaha besar dan ruang komunitas kecil.
Ebo juga menyentil problem di skema distribusi digital: “Streaming digital untuk band dengan pendengar sedikit itu angkanya kecil banget. Makanya kita lebih pilih beli rilisan fisik buat dukung mereka.”
Bagi Rafi sebagai kepala suku dari ruang Omah Jangan Diam Terus, masalahnya terletak pada tempo kebijakan dan kesiapan sistem.
“Di negara lain yang sudah menerapkan ini, sistemnya udah rapih. Di Indonesia, sosialisasinya masih kurang dan terkesan terburu-buru. Apakah royalti ini langsung ke pemegang lisensi? Itu belum jelas,” ungkapnya. Ia bahkan mengutip satir:
“Tidak ada seni yang bisa dipelajari cepat oleh pemerintahan, kecuali seni menguras uang dari kantong rakyat.”
Transparansi Jadi Kunci
Perspektif lainnya juga datang dari Azalea Charismatic, musisi asal Depok yang kini mengelola Smara Terrace di Temanggung, Jawa Tengah. Sebagai musisi, ia sepakat bahwa karya harus dihargai. Namun, sebagai pemilik usaha, ia menilai skema penarikan yang ada belum adil.
“Sekarang dipungut berdasarkan jumlah kursi. Untuk kafe di daerah, ini memberatkan. Karena nggak semua kursi selalu terisi sepanjang tahun. Kenapa tidak berdasarkan, misal, omzet? Data itu kan ada di pajak, jadi minim manipulasi,” ucapnya.
Azalea juga menyoroti efek kebijakan yang berpotensi membuat pelaku usaha beralih ke musik bebas lisensi atau bahkan musik AI, yang justru dapat merugikan musisi lokal.
“Playlist itu pengaruh ke usaha. Banyak review positif karena playlist di kafe kami bikin betah. Jadi harus ada jalan tengah yang adil untuk semua pihak.”
Dari berbagai suara yang terkumpul, bisa ditarik benang bahwa sebagian pemilik ruang komersil di Depok sebenarnya tidak begitu “menolak” membayar royalti, tetapi lebih menuntut transparansi pendistribusian dan penyesuaian skema tarif agar relevan bagi usaha kecil.
Masih menjadi pertanyaan: bagaimana LMKN mendeteksi musik yang diputar? Bagaimana memastikan pembagian tepat sasaran? Dan mengapa tarif dihitung dari luas atau jumlah kursi, bukan dari omset atau malah dari intensitas penggunaan musik itu sendiri?
Isu ini telah memicu seruan agar musisi dan pelaku usaha bersatu mendorong reformasi kebijakan, bukan sekadar memperdebatkan pro-kontra di media sosial. Sebab, di balik setiap lagu yang terdengar di kafe, ada rantai panjang antara pencipta, pengelola, dan kita yang layak mendapat keadilan.