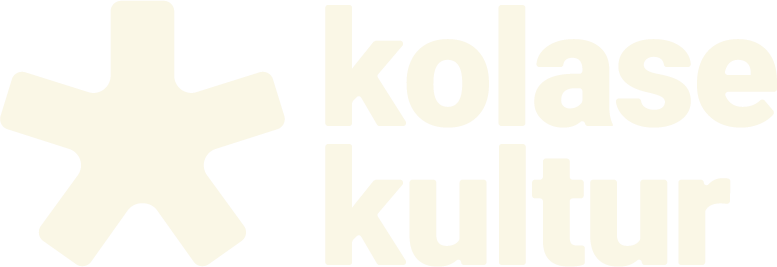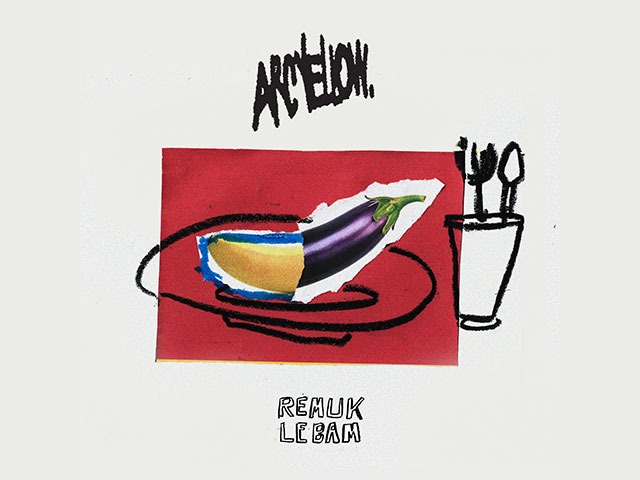Tahun 2021 adalah masa yang cukup menyilaukan bagi perfilman Indonesia, ditandai dengan berbagai penghargaan internasional yang dimenangi oleh beberapa film panjang dan film pendek Indonesia. Diantaranya: Seperti Dendam, Rindu Harus di Bayar Tuntas, Edwin (Golden Leopard, Locarno International Film Festival), Yuni, Kamila Andini (Platform Prize, Toronto International Film Festival), Laut Memanggilku, Tumpal Tampubolon (Sonje Award, …
Jalan Terjal Pekerja Film Indonesia

Tahun 2021 adalah masa yang cukup menyilaukan bagi perfilman Indonesia, ditandai dengan berbagai penghargaan internasional yang dimenangi oleh beberapa film panjang dan film pendek Indonesia. Diantaranya: Seperti Dendam, Rindu Harus di Bayar Tuntas, Edwin (Golden Leopard, Locarno International Film Festival), Yuni, Kamila Andini (Platform Prize, Toronto International Film Festival), Laut Memanggilku, Tumpal Tampubolon (Sonje Award, Busan International Film Festival), dan Dear To Me, Monica Vanesa Tedja (Best Short and Animation Film, First Steps Award). Diiringi dengan film yang turut berkompetisi di festival internasional seperti, Penyalin Cahaya, Wregas Bhanuteja (Busan International Film Festival), Preman, Randolph Zaini (Fantastic Fest), Nussa, Bony Wirasmono (Bucheon International Fantastic Film Festival), Berlabuh, Haris Yulianto (International Short Film Festival Oberhausen), Paranoia, Riri Riza (Bucheon International Fantastic Film Festival), dan Death Knot, Cornelio Sunny (Bucheon International Fantastic Film Festival). Daftar di atas belum tentu merepresentasikan total film panjang maupun film pendek Indonesia yang berkompetisi di festival internasional, tapi paling tidak dapat memberi gambaran mengenai gilap-gemilapnya film Indonesia pada tahun 2021.
Dibalik kegemilangan yang diraih film Indonesia, ada persoalan mendasar dan amat penting yang sudah terlalu lama luput atau bahkan terkesan diabaikan: Hak Pekerja Film. Mungkin momentum yang hadir hari ini juga belum cukup untuk menciptakan kesadaran penuh dalam membenahi kesenjangan yang terjadi di ekosistem film Indonesia. Ada berbagai problem yang dialami pekerja film: bekerja dalam situasi yang rentan, penuh eksploitasi, minim jaminan kesehatan, dan terutama jauh dari perlindungan Negara. Ada yang kopong dalam kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang pernah disebut Presiden Joko Widodo sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Kerentanan yang dialami pekerja film dapat dikaitkan dengan salah satu literatur yang menjelaskan bagaimana kerentanan itu terjadi, Isabell Lorey dalam State of Insecurity: Government of the Precarious (2015: 13-15) menjelaskan mengenai kerentanan. Terdapat tiga dimensi kerentanan. Precariousness merujuk pada kondisi inheren dalam diri manusia dan selalu relasional, yang berarti tidak bersifat individual melainkan sosial. Precarity, relasi dominasi yang nampak dalam hierarki sosial dalam masyarakat. Governmental Precarization, merujuk pada proses perentanan terhadap warga negara dan secara bersamaan memperkuat negara serta melayani produktivitas ekonomi kapitalis. Diskursus tentang ekonomi kreatif di Indonesia hanya hinggap pada romantisasi enterpreneurship. Fleksibilitas pekerjaan yang belakangan menjadi tren. Industri film yang diserukan mampu memajukan perekonomian. Anak-anak muda bakal punya kebebasan dalam industri film. Regenerasi pekerja film yang akan menemui terang. Namun, aspek dasar kerentanan seringkali luput diperhatikan. Ekosistem film saat ini dikuasai oleh waralaba multinasional dengan kapasitas produksi massal. Komunitas yang berukuran mikro jelas akan sangat sulit bersaing.
Lebih jauh, Srnicek telah membahas persoalan ini dalam bukunya yang berjudul Platform Capitalism (2017). Menurut Srnicek, ilusi kebebasan diberikan kepada pekerja dengan menanamkan bahwa mereka telah bebas dari hambatan dalam berkarier dan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi apa pun, bekerja kapan pun dan dimanapun yang mereka mau. Kondisi ini didorong oleh menjamurnya platform, infrastruktur digital yang memungkinkan setiap orang saling terhubung dalam satu waktu dengan lebih gesit. Hal itu juga yang mengubah konsepsi waktu kerja, sehingga pekerja dituntut hadir secara fisik ataupun emosional pada waktu yang bukan jam kerja. Tiba-tiba pada tengah malam, akhir pekan, jam istirahat di kontak atasan untuk menuntaskan pekerjaan yang seharusnya dilakukan di waktu lain. Artinya, batasan waktu kerja dan libur menjadi kabur. Kerentanan pekerja semakin terindividualisasi dan personal. Individualisasi berarti bahwa pekerja film harus mencari pekerjaan selanjutnya di saat pekerjaan sebelumnya selesai. Keberlanjutan kerja inilah yang sangat sulit dijaga di dalam sistem struktural yang tidak beraturan. Perusahaan atau pemberi kerja punya posisi tawar yang lebih tinggi dan selalu memiliki opsi untuk mengganti pekerja. Pekerja harus dipaksa terus menerus mengeluarkan kemampuan terbaiknya dengan resiko yang harus pula ia tanggung sendiri. Dengan begitu posisi yang menguntungkan juga tampak jauh apalagi bagi mereka yang baru memulai dan pemula.
Pada kondisi selanjutnya pekerja film di Indonesia berhadapan dengan kondisi kerja yang penuh ketidakpastian, upah rendah, tanpa jaminan kesehatan ataupun keselamatan kerja. Situasi yang nyata dan terus menjalar sampai saat ini. Ada dua teman yang bercerita mengenai kerentanan bekerja melalui pengalaman mereka bekerja sebagai asisten editor di rumah produksi yang membuat keproduksian film panjang. Pertama, bekerja tanpa kontrak yang jelas. Mereka tidak meminta kontrak lantaran takut aksesnya ke depan terhadap sumber-sumber pemasukan akan terhambat. Ketiadaan kontrak kerja sebenarnya disadari oleh pekerja namun mereka tetap melakukannya lantaran sistem struktural yang menyebabkan mereka tidak memiliki banyak opsi. Kondisi ini menjadi salah satu sumber kerentanan yang dialami pekerja film.
Kedua, tidak adanya jaminan sosial dan asuransi kesehatan. Mereka tidak diberi jaminan kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan dari pemberi kerja. Kondisi ini sangat berpengaruh pada sisi kesehatan pekerja. Belum lagi mereka berdua sebagai asisten editor hampir setiap hari melakukan pekerjaan dari siang hingga larut malam bahkan pagi. Hal itu dikarenakan sistem waktu kerja yang tidak jelas. Konsekuensinya, mereka harus sekuat mungkin menjaga kesehatan agar tidak sakit. Sakit akan membuat mereka mengeluarkan lebih banyak uang dan disinyalir tidak dipekerjakan lagi. Ada peristiwa yang menarik sekaligus memilukan jika menyinggung kesehatan, salah satu teman mendapati dirinya terjangkit Covid-19 pada saat proses penyuntingan film masih banyak yang harus dikerjakan. Waktu itu ia terpaksa harus mengeluarkan uang pribadi yang cukup banyak untuk mengobati penyakitnya. Tak ada bantuan dari pihak pemberi kerja. Di saat sakit itu pula dia ditelpon dan diminta untuk tetap bekerja dari rumah dengan alasan bahan kerjaan masih menumpuk. Ada yang kacau dari cara seperti ini: dia tidak diberi ruang untuk menyembuhkan dirinya.
Ketiga, jam kerja, beban kerja, eksploitasi di tempat kerja. Sebagai pekerja yang tidak terikat kontrak kerja, mereka menyebut bahwa mereka dapat mengatur waktu kerjanya sendiri walaupun tetap melakukan pekerjaan di kantor. Di sisi lain, bisa leluasa mengatur waktu kerja juga menjadi sumber kerentanan. Sebab, mereka bisa bekerja 24 jam dan mesti bersusah payah mendapatkan serta mengatur waktu cuti.
Keempat, upah rendah. Salah satu teman lebih dulu tergabung dalam keproduksian, terhitung sejak hari pertama produksi, dan satunya lagi masuk di saat pasca produksi atas ajakan teman yang lebih dulu bergabung. Yang lebih dulu masuk bekerja selama delapan bulan dan satunya lagi selama enam bulan. Mereka dibayar dengan bayaran yang masih jauh dari kata layak, bahkan ia yang bekerja selama enam bulan hanya dibayar dengan nominal sangat rendah yakni di bawah Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta. Upah yang rendah jelas menjadi kerentanan bagi mereka. Kebutuhan yang semakin tinggi tidak sebanding dengan kelayakan upah.
Kelima, ketidakpastian karier. Dengan apa yang dialami mereka menyadari bahwa tidak ada kepastian karier dalam pekerjaan mereka sebagai pekerja film. Kepastian karier menjadi salah satu kebutuhan mereka dalam menjamin keberlangsungan hidup. Alhasil, mereka lebih sering bekerja sambil memikirkan pekerjaan lain yang lebih memberikan jaminan.
Lebih mengkhawatirkan lagi bagi mereka yang mengikuti proses keproduksian film di industri sebagai anak magang. Di lingkaran film, pekerjaan seringkali didapatkan dari pertemanan dan kepercayaan. Seorang teman yang lebih dulu terjun biasanya mengajak teman lainnya untuk bergabung dalam keproduksian, setelah itu akan dilabeli anak magang. Seseorang yang baru pertama kali terjun ke dalam industri film dengan modal pernah membuat film pendek kebanyakan menghiasi aktivitas perekrutan. Mereka yang dipandang sebagai anak magang dianggap tidak layak untuk menanyakan kontrak kerja dan dibayar dalam jumlah yang terbilang tidak sebanding dengan apa yang dilakukan. Ada stigma yang berkelindan pada mereka yang menagih haknya, “kalo baru masuk industri ataupun masih anak magang jangan nanya-nanya soal kontrak kerja dulu, nanti dianggap sombong dan tidak dipakai lagi”.
Padahal, semua hak yang tertera di atas wajib didapatkan pekerja dan peserta magang, sebab sudah ada hukum yang mengatur itu semua, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Permagangan di Dalam Negeri. Kejadian di atas dan temuan lainnya sudah semestinya membuka mata dan telinga bahwa di balik hingar-bingar prestasi perfilman Indonesia, revolusi 4.0, dan tetek-bengek lainnya yang menyilaukan, ada kondisi pekerja yang memprihatinkan. Selain itu, kehadiran Negara masih bercokol dengan regulasinya yang tidak memihak pekerja dan terus melakukan romantisasi yang berkutat pada citra positif industri film. Kerentanan yang terjadi seperti tekanan untuk kerja tanpa kontrak ataupun di luar kontrak, siap dihubungi kapan pun, kerja melampaui jam normal, tak punya kebebasan mengambil cuti, dan bekerja di bawah ketidakpastian karier tentu saja adalah pengalaman kolektif yang pada dasarnya tidak hanya dialami pekerja film, tetapi juga pekerja lainnya.
Tonggak pencapaian film Indonesia di dunia internasional mulai dari tahun 2021 mungkin adalah satu hal yang penting bagi kemajuan ekosistem film Indonesia. Namun, di balik hiruk-pikuk kecemerlangan film Indonesia yang berhasil berkompetisi dan memenangkan penghargaan di festival internasional, sudah saatnya kita membicarakan persoalan mengenai pemenuhan hak para pekerja film. Saat ini, Negara dan para pemilik modal di industri film masih sekadar melanggengkan ilusi kebebasan yang terus menerus digemborkan untuk menyembunyikan sederet kerentanan yang ada di dalamnya. Perlu adanya identifikasi yang merata dalam pemetaan ekosistem film di Indonesia, dan yang tak kalah penting juga bahwa eksosistem film tak hanya berisikan pembuat film, tetapi ada banyak orang di dalamnya, dari ekshibisi hingga pengarsipan. Kita perlu mengelaborasi faktor-faktor yang ada sehingga membuat para pekerja film merasakan kebutuhan untuk berserikat. Bagaimana para pekerja mengidentifikasi kondisi mereka saat ini, dan seperti apa mereka melihat kebutuhan untuk bergabung dengan serikat pekerja. Untuk melihat sejauh mana posisi pekerja dalam industri film dapat mempengaruhi kesadaran kelas, juga memahami bagaimana proses kelas pekerja telah terprekarisasi secara masif. Baik-baik saja jika berharap, tetapi kita perlu menengok realita yang ada di depan mata. Ketika kita mengeluh-eluhkan regenerasi pembuat film di Indonesia yang terasa mandek, barangkali kita perlu menjawab sebuah pertanyaan terlebih dahulu: apa kita sudah cukup peduli pada kesejahteraan para pekerja film selama ini, dan apakah betul kita tidak mengabaikan mereka di atas segala manfaat yang telah dikantongi.